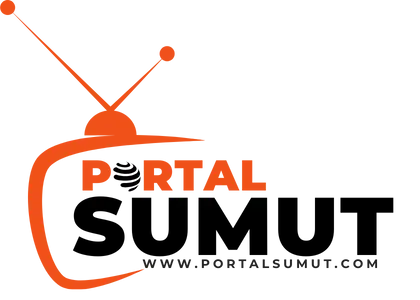Pendidikan sejatinya adalah ikhtiar peradaban untuk membentuk manusia paripurna, yakni insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu memberi manfaat luas bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Namun, realitas hari ini menunjukkan bahwa arah pendidikan telah bergeser jauh dari orientasi spiritual dan sosialnya. Dalam banyak kasus, pendidikan telah menjadi mesin produksi tenaga kerja semata, bukan tempat pembentukan jiwa dan karakter. Ketika keberhasilan siswa hanya dinilai dari nilai akademik dan status pekerjaan, maka sesungguhnya pendidikan telah kehilangan jiwanya. Bahkan UNESCO (2015) menekankan bahwa pendidikan harus membentuk kepribadian utuh (whole person), bukan hanya manusia yang pintar secara akademik.
Kritik pertama yang perlu disuarakan keras adalah terhadap orang tua, sebagai pendidik pertama dan utama. Alih-alih menjadi pengarah kehidupan anak-anaknya, banyak orang tua hari ini justru hanya menjadi “penyuplai fasilitas pendidikan” tanpa terlibat dalam pembentukan nilai dan karakter. Cita-cita anak direduksi menjadi “ingin jadi dokter, insinyur, PNS,” tetapi tidak pernah ditanyakan: “Untuk apa kamu menjadi itu semua?” Konsep “jadi apa” mendorong anak tumbuh dalam orientasi egoistik untuk status, gaji, dan gengsi. Sebaliknya, pertanyaan “untuk apa” menumbuhkan nilai-nilai altruistik dan kolaboratif. Mindset ini yang seharusnya dibangun dalam pendidikan berbasis visi profetik (Abdullah, 2019).
Sebagai institusi yang dipercaya masyarakat, sekolah pun tak lepas dari kritik tajam. Sekolah hari ini lebih mirip pabrik, dengan sistem yang mengedepankan seragamitas, pengukuran kognitif, dan penyeragaman standar. Ujian nasional, asesmen standar, dan ranking kelas justru mengkerdilkan dimensi afektif dan psikomotorik siswa. Padahal, tujuan pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah “mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Sayangnya, dalam praktiknya, orientasi moral dan sosial ini tenggelam di bawah tumpukan soal-soal kognitif.
Kritik terhadap sekolah juga muncul karena perannya yang seringkali tidak adaptif terhadap perubahan sosial. Sementara dunia terus bergerak dinamis, sekolah sering terjebak dalam kurikulum kaku yang tidak menjawab tantangan zaman. Keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas (4C) belum menjadi budaya belajar di sekolah. Bahkan lebih parah, nilai-nilai agama dan kebangsaan diajarkan dalam bentuk hafalan, bukan keteladanan dan penghayatan. Ini melahirkan generasi yang tahu nilai tetapi tidak menjalankannya. Sebagaimana dikritik oleh Freire (1970), sekolah menjadi tempat “banking education” di mana siswa hanya menerima, menyimpan, dan mengulang informasi.
Dampak dari kegagalan fungsi pendidikan ini begitu nyata dalam realitas sosial: meningkatnya korupsi, rendahnya empati sosial, dan lemahnya kepedulian terhadap nasib bangsa. Banyak lulusan terbaik justru tidak menjadi solusi bangsa, melainkan bagian dari masalah. Pengetahuan yang diperoleh tidak diiringi dengan arah moral, sehingga menjadi alat manipulasi bukan pemberdayaan. Di sinilah pentingnya landasan iman, takwa, dan akhlak mulia dalam pendidikan. Tanpa fondasi ini, pengetahuan menjadi pedang tanpa kendali. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Attas (1993), ilmu yang tidak disucikan oleh nilai akan menjadi sumber kerusakan.
Dalam konteks ini, keluarga dan sekolah harus berani melakukan introspeksi bersama. Pendidikan bukan sekadar tanggung jawab lembaga formal, tetapi adalah ruang sinergi antara rumah dan sekolah. Orang tua harus kembali mengambil peran aktif sebagai pendidik nilai, bukan hanya pendorong prestasi. Sekolah harus membuka diri untuk berkolaborasi dengan keluarga, menjadikan proses belajar sebagai gerakan sosial, bukan rutinitas administratif. Kurikulum harus memberi ruang bagi pembelajaran berbasis proyek kemanusiaan, bukan hanya hafalan rumus. Perubahan paradigma ini harus segera dilakukan bila bangsa tidak ingin terus mencetak generasi apatis dan individualistik.
Solusinya adalah membangun pendidikan berbasis visi kolektif yang mengintegrasikan antara iman, ilmu, dan amal. Pendidikan harus mulai dengan membangun identitas dan orientasi spiritual siswa. Guru dan orang tua perlu bersama-sama menyemai misi hidup anak sejak dini: “Untuk apa kamu hidup?”, “Masalah apa yang ingin kamu selesaikan dalam kehidupan ini?” Ini akan melahirkan generasi dengan visi misi, bukan hanya ambisi pribadi. Mereka akan memilih profesi bukan karena gaji, tetapi karena ingin menyelesaikan problem sosial dan inilah bentuk pendidikan yang transformatif (Sahlberg, 2018).
Refleksi akhir dari semua ini adalah kita tidak bisa berharap pada sistem yang gagal jika kita sendiri sebagai orang tua dan pendidik tidak berbenah. Pendidikan bukan tentang gedung mewah, peringkat internasional, atau nilai rapor, tetapi tentang dampak kebermanfaatan hidup seseorang di tengah masyarakatnya. Selama kita tidak memaknai ulang pendidikan sebagai proses pembentukan misi hidup yang bermoral dan profesional, maka output pendidikan hanyalah manusia terdidik yang kehilangan arah. Mari berhenti bertanya kepada anak: “Kamu mau jadi apa?” dan mulailah bertanya: “Untuk apa kamu ada?”