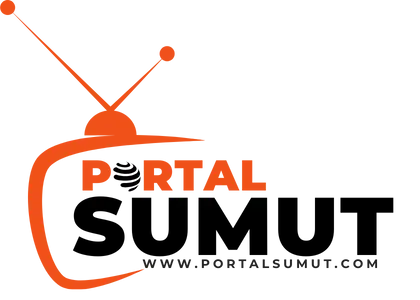Pemerintah pusat tampaknya kembali salah langkah dalam menangani urusan Aceh. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, empat pulau Panjang, Lipan, Mangkir Besar, dan Mangkir Kecil yang selama ini masuk wilayah Aceh Singkil, tiba-tiba dipindah ke wilayah Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Alasan yang disampaikan hanyalah “penyesuaian batas administratif.” Namun, di Aceh, persoalan ini tidak sesederhana itu. Empat pulau itu bukan sebatas daratan kosong mereka simbol identitas dan harga diri.
Aceh bukan sekadar provinsi biasa. Ia adalah daerah yang darahnya telah tumpah demi hak mengelola diri sendiri. Setelah lebih dari dua dekade konflik bersenjata, kesepakatan damai Helsinki pada 15 Agustus 2005 menjadi jembatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia. Salah satu butir penting dari MoU tersebut adalah: Aceh berhak mengatur dirinya sendiri, berdasarkan batas wilayah per 1 Juli 1956. Artinya, perubahan batas administratif sekecil apa pun harus melalui konsultasi, kesepakatan bersama, dan melibatkan rakyat Aceh.
Sayangnya, langkah Tito Karnavian selaku Mendagri dan manuver Bobby Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara justru mengabaikan seluruh sensitivitas itu. Mereka membaca Aceh dengan kacamata administratif, bukan dengan lensa historis. Seakan Aceh hanyalah bagian dari file Excel yang bisa dipotong dan tempel sesuka hati. Lebih dari sekadar arogansi kekuasaan, ini mencerminkan kecerobohan membaca sejarah dan meremehkan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh.
Muzakir Manaf, mantan Panglima GAM dan tokoh sentral dalam kesepakatan damai Helsinki, sudah menyuarakan sikap keras. Bagi beliau, pemindahan empat pulau itu adalah bentuk pengingkaran terhadap ruh kesepakatan yang sudah menyelamatkan Indonesia dari konflik berkepanjangan. Ia tidak bicara sebagai kepala daerah, tapi sebagai saksi hidup sejarah Aceh. Ketika pusat memaksakan kehendak secara sepihak, bukan hanya wilayah yang dicederai melainkan juga martabat.
Ironisnya, dalam sebuah pertemuan yang disorot publik, Bobby Nasution sempat menawarkan kepada Muzakir Manaf untuk mengelola bersama empat pulau tersebut, seolah ini hanya perkara investasi dan kolaborasi antar daerah. Pernyataan ini menunjukkan ketidaksensitifan politik dan minimnya pemahaman terhadap sejarah serta hukum yang mengikat Aceh. Lebih jauh lagi, ajakan itu mencerminkan tendensi kekuasaan yang menyepelekan prinsip-prinsip hukum tata negara. Kepmendagri, bagaimanapun bentuknya, tidak boleh bertentangan dengan perjanjian damai yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketika seorang kepala daerah, apalagi gubernur, gagal membaca bahwa ada norma hukum yang lebih tinggi dari keputusan menteri, maka ini bukan lagi soal teknis administratif, tapi krisis etika dan logika konstitusional. Bukan hanya menyinggung Aceh, tapi juga mencederai asas negara hukum yang menjadi fondasi republik ini.
Lebih janggal lagi, kebijakan ini hadir di tengah sorotan publik terhadap kasus tambang nikel di Raja Ampat dan Papua. Saat masyarakat menuntut keadilan ekologis dan hak hidup atas tanah mereka sendiri, pusat justru menyibukkan diri dengan memindahkan empat pulau kecil yang tidak sedang bermasalah. Ironisnya, masyarakat sekitar tambang yang menjanjikan “investasi hijau” justru menjadi korban penggusuran, pengabaian hak, dan kemiskinan struktural. Pola-pola eksploitasi semacam ini selalu berulang: sumber daya dihisap, masyarakat dipinggirkan, lalu pusat datang dengan narasi “pembangunan nasional.”
Jika empat pulau saja bisa “dibegal” tanpa persetujuan rakyat Aceh, apa yang menjamin Jakarta tak akan bertindak serupa terhadap hak-hak daerah lain di masa depan? Inilah wajah baru kolonialisme administratif: tak lagi memakai senjata, tapi pakai stempel dan keputusan menteri. Ketika pusat bisa semena-mena mencaplok wilayah hanya karena peta digital dan kesepakatan para elite, maka masa depan otonomi daerah di republik ini sedang dipertaruhkan. Jangan sampai demokrasi lokal yang diperjuangkan dengan darah dan air mata, diruntuhkan oleh birokrasi yang kering sejarah dan rakus kuasa.
Pemerintah pusat harus tahu: Aceh bukan sekadar soal koordinat. Ini adalah wilayah yang berdamai tanpa kalah. Ketika masyarakat Aceh memprotes pemindahan wilayah, mereka tidak hanya bicara tentang peta mereka bicara tentang memori kolektif yang telah mereka bangun dengan penuh luka dan pengorbanan. Jika semangat Helsinki dihianati, maka konsekuensinya bukan hanya politis, tapi juga emosional dan sosial.
Jusuf Kalla, tokoh penting dalam perundingan damai Helsinki, bahkan menyebut bahwa Kepmendagri tersebut “cacat formil.” Ini bukan pernyataan sembarangan. Ketika sosok sekelas JK angkat suara, maka sudah sepatutnya Jakarta berhenti bersikap defensif. Kita tidak butuh lagi konflik horizontal karena kecerobohan vertikal.
Langkah pemindahan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara bukan hanya merusak tatanan administratif, tetapi juga menginjak-injak kearifan lokal yang menjadi ruh hubungan antardaerah di Tanah Rencong dan Tanah Batak. Dalam budaya Aceh, wilayah adalah bagian dari kehormatan yang tak bisa dinegosiasi, sedangkan di Sumatera Utara khususnya dalam filosofi adat Batak soal batas dan tanah selalu diputuskan lewat musyawarah adat yang menjunjung tinggi martabat. Ketika keputusan sepihak datang dari Kemendagri, dan para elite Sumut menerima begitu saja tanpa mempertimbangkan akar budaya dan dialog lintas komunitas, maka yang terjadi bukan sinergi, melainkan dominasi. Ini mencerminkan bahwa para pengambil kebijakan dan sebagian tokoh pejabat Sumut hari ini tak lagi berpijak pada nilai-nilai lokal, dan lebih tunduk pada tekanan kekuasaan pusat yang steril dari kearifan sejarah. Apa gunanya pejabat daerah jika tak mampu memahami narasi panjang rakyat yang mereka wakili?
Pernyataan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara yang secara terbuka meminta masyarakat untuk “mematuhi keputusan menteri” justru memperkeruh suasana dan memperlihatkan ketidakmampuan legislatif daerah dalam membaca situasi. Bagaimana mungkin seorang pimpinan lembaga legislatif bisa membenarkan keputusan yang jelas-jelas cacat formil dan bertentangan dengan semangat perdamaian nasional? Alih-alih menjadi penengah dan penjaga konstitusi, DPRD Provinsi justru menjadi corong birokrasi pusat yang sedang dipertanyakan legitimasi dan etikanya. Apakah ini karena tekanan politik dari elite pusat, atau memang karena minimnya literasi hukum dan sejarah di kalangan wakil rakyat kita? Ketika wakil rakyat tidak lagi berpihak pada keadilan dan malah membungkam suara publik demi kenyamanan jabatan, maka publik pun berhak mempertanyakan: masih pantaskah lembaga ini dipercaya sebagai penyambung lidah rakyat? Keberpihakan membabi buta semacam ini bukan hanya menyakitkan Aceh, tapi juga mencederai integritas demokrasi daerah itu sendiri.
Jika Tito dan Bobby masih mengira mereka bisa memperdaya Aceh dengan pendekatan teknokratik, mereka salah besar. Politik Aceh adalah politik kehormatan. Kedaulatan wilayah bukan sekadar dokumen negara ia adalah bagian dari jiwa rakyatnya. Dan jika Bobby tidak mampu lebih bijak menyelesaikan persoalan ini untuk menjaga marwah kearifan budaya Sumatera Utara maka tokoh adat budaya Sumut wajib terlibat dalam menyelesaikan persoalan ini secara Arif sesuai nilai warisan leluhur yang bijak membangun kekerabatan dan keluargaan. Karena sejarah telah membuktikan: Aceh tidak pernah diam saat harga dirinya dilukai.
———————–
Penulis merupakan tokoh Budayawan Batak Pomparan Ni Raja Silahisabungan Sumatera Utara